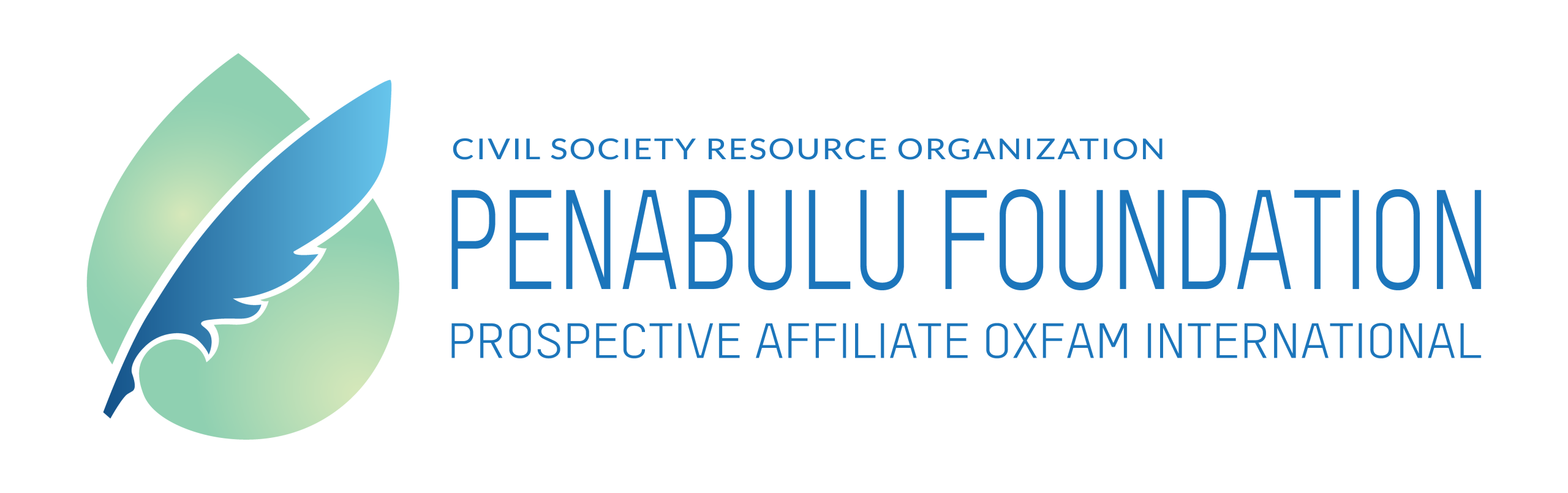TAHUN 2018, jurnal terkenal Antiviral Research menerbitkan artikel berjudul Broad-spectrum antiviral activity of the eIF4A inhibitor silvestrol against corona-and picornaviruses. Artikel ini menjajaki penggunaan senyawa alami silvestrol sebagai potensi solusi dalam menangani virus corona. Senyawa silvestrol sendiri diekstrak dari Aglaia, sejenis mahoni yang tumbuh terbatas di Kalimantan. Virus yang dimaksud tentu bukan virus corona jenis baru yang menyebabkan penyakit Covid-19, melainkan virus corona yang menyebabkan penyakit MERS (Middle East respiratory syndrome coronavirus). Selain virus corona, penelitian ini juga menyasar pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus ebola (Ebola Virus Disease).
TAHUN 2018, jurnal terkenal Antiviral Research menerbitkan artikel berjudul Broad-spectrum antiviral activity of the eIF4A inhibitor silvestrol against corona-and picornaviruses. Artikel ini menjajaki penggunaan senyawa alami silvestrol sebagai potensi solusi dalam menangani virus corona. Senyawa silvestrol sendiri diekstrak dari Aglaia, sejenis mahoni yang tumbuh terbatas di Kalimantan. Virus yang dimaksud tentu bukan virus corona jenis baru yang menyebabkan penyakit Covid-19, melainkan virus corona yang menyebabkan penyakit MERS (Middle East respiratory syndrome coronavirus). Selain virus corona, penelitian ini juga menyasar pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus ebola (Ebola Virus Disease).
Artikel tersebut menunjukan bahwa upaya menemukan obat anti-virus berbasis keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik menjadi perhatian serius para peneliti dunia, terutama dari negara maju. Sumber pencaharian obat ini umumnya di negara berkembang yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi.
Upaya seperti ini sebenarnya bukan hal baru, bahkan telah berkembang pesat sejak tahun 1980an. Saat itu perusahaan farmasi dari negara maju melakukan investasi besar terhadap sumber obat-obatan yang berasal dari keanekaragaman sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat. Reid (1993) menyebutnya bioprospecting.
Pada umumnya eksplorasi sumber obat-obatan berbasis sumber daya genetik dibarengi dengan penelusuran terhadap pengetahuan masyarakat lokal. Menurut Cotton (1996), jika penelitian dilakukan secara acak, tanpa diiringi dengan pengetahuan tradisional, maka probabilitas ditemukannya senyawa aktif bermanfaat akan sangat kecil dan membutuhkan waktu dan biaya besar. Sebaliknya, jika penelitian didasari oleh pengetahuan masyarakat lokal yang telah terbukti hingga lintas generasi, maka probabilitas tersebut akan meningkat.
Sayangnya pengetahuan masyarakat lokal sering diabaikan ketika bioprospecting masuk pada fase komersialisasi. Padahal pengetahuan tersebut ditemukan dan dipelihara selama ribuan tahun oleh masyarakat lokal. Dengan kata lain, penemu asli sebenarnya adalah masyarakat lokal. Kondisi ini oleh Pat Mooney (1993) disebut dengan biopiracy, yaitu perampasan sumber daya genetik dan pengetahuan lokal oleh individu/lembaga untuk memperoleh kontrol eksklusif melalui hak paten.
Kasus biopiracy yang cukup terkenal adalah hak paten penggunaan kunyit untuk pengobatan luka yang diperoleh oleh ilmuwan Amerika tahun 1995. India mengajukan keberatan atas hak paten ini karena masyarakat India telah menggunakan kunyit sebagai salep luka selama ribuan tahun. Paten tersebut akhirnya dibatalkan tahun 1997.
Sementara kasus biopiracy di Indonesia salah satunya terjadi tahun 1999, ketika perusahaan kosmetik asal Jepang dituntut untuk membatalkan paten atas pemanfaatan rempah-rempah asal Indonesia untuk produk-produk anti penuaan (anti-aging). Perusahaan ini mengajukan 51 permohonan paten tumbuhan obat dan rempah asli Indonesia di kantor paten Jepang, serta paten lain di Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia. Melalui tuntutan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, perusahaan ini akhirnya membatalkan permohonan registrasi paten tersebut.
Peluang dan Tantangan Indonesia
Menurut AIPI (2019), gabungan biodiversitas daratan dan lautan, termasuk jasad reniknya, menjadikan Indonesia negara dengan biodiversitas terkaya di planet bumi. Kekayaan biodiversitas ini telah menginspirasi karya-karya besar kelas dunia, seperti karya Rumphius, Wallace, dan Eijkman.
Georg Eberhard Rumphius (1627-1702), menghasilkan magnum opus berjudul Herbarium Amboinense yang berkontribusi besar dalam pengembangan sistem penamaan ilmiah (taksonomi) modern. Demikian juga Alfred Russel Wallace yang membangun teori evolusi (survival of the fittest) setelah menjelajah dan mendokumentasikan keanekaragaman hayati Nusantara selama 8 tahun (1854–1862). Christiaan Eijkman bahkan mendapat hadiah Nobel Kedokteran tahun 1929 setelah laboratorium yang dipimpinya menemukan vitamin B1 sebagai anti beri-beri dari kulit air beras. Laboratorium ini sekarang dikenal dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang berperan besar dalam uji Covid-19.
Dewasa ini penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh Rumphius, Wallace, dan Eijkman masih terus dilakukan, dengan skala yang beragam. Beberapa proyek penelitian internasional dilakukan melalui kerjasama formal dengan lembaga penelitian Indonesia, namun banyak juga penelitian dilakukan secara ilegal.
Tahun 2019 lalu, misalnya, beberapa media memberitakan kasus pengambilan lebih dari 200 sampel tumbuhan dan satwa liar tanpa izin oleh warga negara asing dari Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat.
Di tahun yang sama, Kemenristek mendeportasi 10 peneliti asing yang melanggar aturan penelitian di Indonesia.
Banyaknya peneliti asing yang masuk ke Indonesia bisa dipahami karena penelitian dalam konteks bioprospecting berhilir pada komersialisasi. Sebagai gambaran, nilai ekonomi bioprospecting dunia diperkirakan mencapai USD 500 milyar per tahun yang mencakup sektor farmasi, produk pertanian, tanaman hias, kosmetik, dan berbagai produk bioteknologi lainnya.
Karena itu diperlukan regulasi yang mampu melindungi kepentingan lembaga penelitian, masyarakat lokal, dan pelaku usaha. Tanpa adanya regulasi ini, maka biopiracy akan semakin marak di Indonesia.
Pada level global, dalam rangka memerangi biopiracy, para pemimpin dunia telah menyepakati Protokol Nagoya pada pertemuan para pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP-10 CBD) tahun 2010 di Nagoya, Jepang. Protokol Nagoya mengatur Access and Benefit Sharing (ABS), yaitu pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Protokol ini mengatur akses dan pembagian keuntungan antara negara maju (sebagai pengguna sumber daya genetik yang menguasai sains dan teknologi) dan negara berkembang (sebagai penyedia sumber daya genetik).
Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 (UU 11/2013) Tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).
Namun yang menjadi catatan, UU 11/2013 masih merupakan penetapan prosedural bahwa Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya, belum menjadi regulasi dalam arti material (substantif). Karena itu diperlukan Undang-Undang lain yang mentransformasikan norma Protokol Nagoya ke dalam hukum nasional.
Sebenarnya sudah pernah disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mentransformasikan norma Protokol Nagoya, yaitu RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik (PSDG). RUU ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2005-2009, periode 2010-2014. dan periode 2015-2019. Namun statusnya hingga kini masih RUU.
Materi RUU PSDG juga sempat masuk kedalam draft revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU 5/1990) Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun revisi UU 5/1990 yang diinisiasi oleh DPR-RI ini pun mengalami hal yang sama dengan RUU PSDG setelah pemerintah menolak membahasnya.
Periode DPR-RI sekarang (2020-2024) kembali memasukkan RUU PSDG dalam Prolegnas dengan judul baru, yaitu RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.
Kita berharap DPR RI periode 2020-2024 bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang tertunda cukup lama ini. Kehadiran Undang-Undang ini akan mendorong pengelolaan sumber daya genetik lebih komprehensif dan Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dapat berkontribusi besar dalam penemuan berbagai obat atau vaksin, termasuk untuk virus corona.
Sumber: www.kehati.or.id