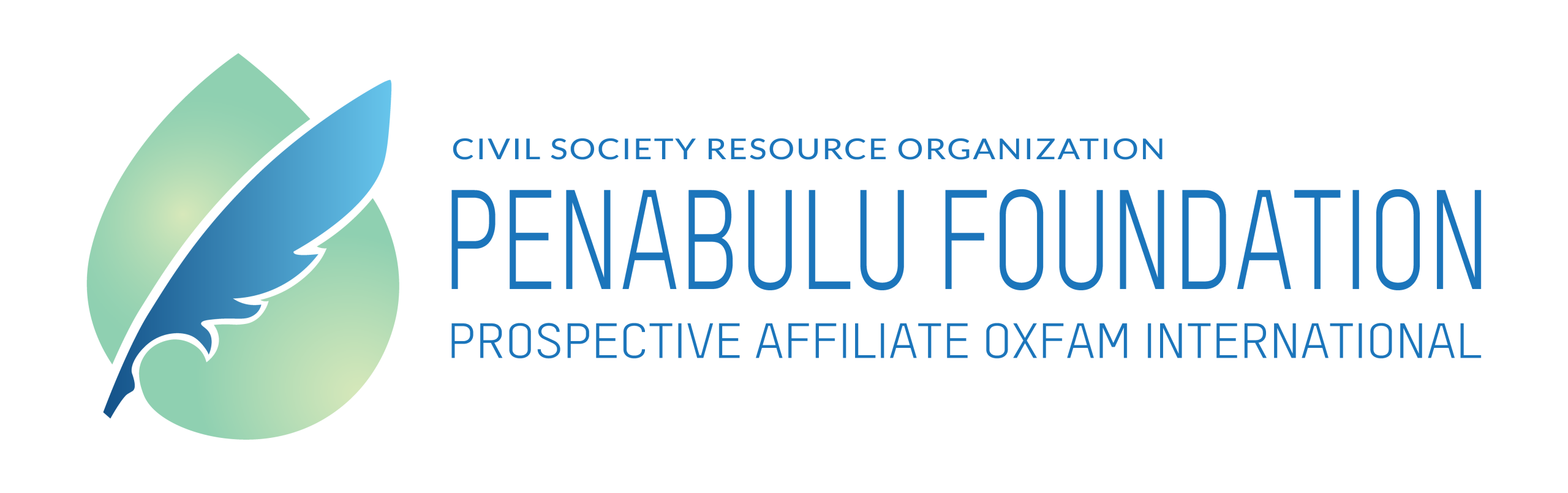Kalau tak segera diluruskan, istilah Ormas akan jadi istilah payung yang membuat seluruh organisasi di sektor masyarakat sipil jadi Ormas.
oleh: Aryanto Nugroho

Apapun kegiatan organisasinya, mulai dari penelitian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, panti asuhan, advokasi, penyayang hewan, relawan bencana dan lain sebagainya, saat ini berpotensi dikategorikan sempit sebagai Organisasi Kemasyarakatan alias “Ormas”. Ada potensi salah arah kebijakan untuk “meng-ormas-kan” seluruh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia. Merespon ini, ada OMS yang bingung, ada yang menolak, ada yang terpaksa ikut, ada juga yang merasa semua baik-baik saja.
Persoalan ini timbul lagi sejak dibangkitkannya UU Ormas tahun 2013, yang dibuat makin runyam dengan Perppu Ormas tahun 2017. UU Ormas terkini mencampuradukkan badan hukum Yayasan dan Perkumpulan dalam pengertian Ormas, sehingga menimbulkan kerancuan dalam praktiknya. Patut diduga, ke depan akan terjadi pergeseran makna atas istilah Ormas. Kalau tak segera diluruskan, istilah Ormas akan jadi istilah payung yang membuat seluruh organisasi di sektor masyarakat sipil jadi Ormas.
Dalam politik hukum, istilah tak pernah sekadar jadi istilah. Menggunakan istilah Ormas untuk jadi padanan OMS, pasti mempengaruhi konsep, pendekatan, dan praktik masyarakat sipil ke depan. Jangan lupa, istilah Ormas punya beban sejarah sendiri. Setelah sekian lama hadir di tengah masyarakat, istilah Ormas tentunya sudah punya kesan dan konotasi sebagai jenis dan praktik organisasi tertentu.
Dengan jadi Ormas, organisasi akan terikat pada semua aturan yang tercantum dalam UU Ormas, termasuk segala larangan dan sanksinya. Sebagai bagian dari “Paket Undang-Undang Politik” yang cetak birunya dibuat pada masa Orde Baru, UU Ormas bertaburan pasal-pasal larangan yang membatasi ruang gerak.
Sejak Perppu Ormas tahun 2017, pembubaran Ormas bisa dilakukan pemerintah tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu. Sejauh ini sudah ada tiga organisasi yang dibubarkan tanpa pengadilan: Hizbut Tahrir Indonesia, Badan Hukum Perkumpulan ILUNI-UI, dan Front Pembela Islam. Banyak yang belum sadar, bahwa dengan adanya upaya meluaskan tafsir definisi Ormas, ancaman pembubaran sepihak itu kini bisa tertuju pada semua organisasi yang bergerak di sektor masyarakat sipil.
Risiko-risiko ini perlu dipahami terlebih dahulu oleh OMS yang hendak mendefinisikan organisasinya sebagai Ormas. Jangan sampai OMS lupa konteks, dan langsung mengaku sebagai Ormas, misalnya hanya untuk memenangkan Ormas Awards atau sekadar supaya bisa ikut dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Keputusan untuk mendefinisikan diri sebagai Ormas, harus ditimbang masak-masak oleh OMS lengkap dengan segala risikonya.
Memahami Masyarakat Sipil
Masyarakat Sipil memang bukan konsep yang sederhana. Mungkin karena ada kata “sipil”, tak jarang orang mengira bahwa ini soal dikotomi Sipil-Militer. Konsep Masyarakat Sipil alias Civil Society bersifat multi-dimensi, dan penuh perdebatan. Konsep ini bisa dirunut dua ribuan tahun ke belakang, mulai dari Aristotle (politiken koinonian), Cicero (societas civilis), Hobbes, Locke, Hegel, Marx, Ferguson, de Tocqueville, Gramsci dan sederetan pemikir penting lainnya. Diskusi tentang Civil Society diwarnai perdebatan dari para pemikir klasik maupun modern, yang hadir dari berbagai spektrum pemikiran.
Buntutnya, menerjemahkan Civil Society ke bahasa Indonesia juga jadi tak sederhana. Di Indonesia, ada Nurcholis Madjid yang menerjemahkan Civil Society sebagai “Masyarakat Madani”, Soetandyo Wignjosoebroto dengan “Masyarakat Warga”, atau Mansour Fakih yang memilih terjemahan “Masyarakat Sipil”. Semua dengan alasan dan penjelasannya masing-masing.
Dalam pembahasan tentang sektor, masyarakat sipil dibedakan dari sektor negara (state) dan sektor pasar (market). Menariknya, sektor masyarakat sipil juga punya nama lain, yang mencerminkan keluasan lingkup dan perbedaan cara pandang atas sektor ini, yaitu: Sektor Nirlaba (Nonprofit Sector), Sektor Ketiga (Third Sector), Sektor Kesukarelaan (Voluntary Sector) dan berbagai nama lainnya.
Salah satu aktor di sektor masyarakat sipil adalah Civil Society Organisation (CSO), atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). OMS meliputi beragam jenis organisasi, mulai dari organisasi berbasis keyakinan (faith-based organisations), organisasi non-pemerintah (Ornop)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi berbasis komunitas (community-based organisations), lembaga riset independen (independent research institutes), organisasi keanggotaan berbasis massa (mass-based membership organisations), organisasi relawan (volunteer organisations) dan lain sebagainya.
Salamon, Sokolowski, dan List (2003) mendefinisikan ciri-ciri entitas yang ada dalam sektor masyarakat sipil sebagai: 1) Organizations, memiliki struktur, dan keteraturan dalam beroperasi (baik formal maupun informal), 2) Private, bukan bagian dari negara, 3) Not profit distributing, alias nirlaba, 4) Self-governing, ada mekanisme tata kelola internal yang mandiri, 5) Voluntary, keterlibatan ataupun keanggotaan dalam organisasi itu bersifat sukarela, bukan karena suatu kewajiban.
Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa OMS tidak bisa begitu saja disempitkan jadi Ormas. Semesta OMS jelas lebih luas dari Ormas. Menimbang luas dan keragaman OMS, bisa dipastikan bahwa baju Ormas bakal kesempitan bila dipaksakan. Arus untuk memadankan istilah Ormas dengan pengertian OMS, berpotensi untuk menimbulkan masalah lebih besar dari sekadar soal pilihan istilah.
Perebutan Tafsir
Tanpa pemahaman atas konteks gerakan masyarakat sipil, sikap memadankan istilah Ormas dengan OMS, bisa dipandang tak masalah. Padahal, istilah Ormas tak lepas dari jejak kelam rezim Orde Baru yang mengedepankan stabilitas politik dengan mengontrol dinamika organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
Kita perlu ingat bagaimana konsep-konsep Orde Baru seperti “Asas Tunggal” ataupun “Wadah Tunggal” dalam UU No.8/1985 tentang Ormas, digunakan untuk memberangus organisasi. Persoalan “Asas Tunggal”, sempat membuat Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) tidak diakui keberadaannya dan kegiatannya pun sempat dilarang. Sementara “Wadah Tunggal” intinya mendorong organisasi sejenis agar berhimpun hanya dalam satu wadah pembinaan. Dalam praktiknya, rezim Orde Baru tak berkenan atas organisasi tandingan yang di luar kendalinya.
Percobaan penguasa untuk memadankan istilah Ormas dengan OMS, sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1985. Definisi Ormas dalam Pasal 1 UU Ormas 1985 mencakup pengertian luas, yaitu: “…organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.
Dengan definisi seluas itu, bisa diartikan bahwa segala jenis organisasi bentukan masyarakat di sektor masyarakat sipil bisa dikategorikan sebagai Ormas. Walau tak tegas tertulis, tapi definisi luas ini dengan sendirinya berupaya memadankan istilah Ormas dengan OMS.
Menariknya, percobaan perebutan tafsir itu nampaknya disadari dan berhasil dilawan oleh aktivis LSM tahun 80-an. Penggalan sejarah perlawanan tafsir itu terekam dalam buku Eldridge (1995), yang menceritakan bahwa kalangan LSM saat itu berhasil menentang penerapan UU Ormas 1985 atas LSM, dengan menyatakan bahwa UU Ormas hanya mengatur organisasi berbasis massa, sehingga LSM tidak ikut masuk dalam pengertian Ormas.
Tafsir bahwa UU Ormas hanya mengatur organisasi berbasis massa dan mengecualikan LSM, menurut Eldridge, akhirnya didukung oleh Soepardjo Roestam (saat itu Menteri Dalam Negeri). Eldridge menduga sikap pemerintah Orde Baru yang tidak mengejar detail pengaturan UU Ormas terhadap LSM saat itu, adalah karena penerimaan yang relatif baik dari kalangan LSM atas asas Pancasila. Namun Eldridge juga mencatat, walau perlawanan tafsir itu bisa membuat LSM bertahan hidup dalam suasana politik yang membatasi, tapi hal itu menyisakan ketidakjelasan berkepanjangan atas landasan hukum keberadaan LSM.
Soal istilah “LSM” pun tak lepas dari upaya perebutan istilah oleh rezim Orde Baru. Mansour Fakih (1996) mencatat sikap kritis sebagian aktivis masa itu yang lebih memilih istilah Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) dibanding istilah LSM, karena dipandang sebagai upaya penjinakan oleh penguasa. Hadiwinata (2003) menjelaskan konteks kelahiran istilah LSM pada tahun 1980, karena pemerintah Orde Baru keberatan dengan istilah Ornop yang merupakan terjemahan langsung dari Non-Governmental Organisations (NGOs).
Kembali ke soal istilah Ormas, memasuki era 90-an, meskipun pemerintah bertahan dengan definisi luas, dapat dikatakan sejak itu praktik pengertian Ormas terbatas pada organisasi berbasis keanggotaan yang berjumlah besar (berbasis massa). Bisa jadi, di titik inilah asal munculnya salah kaprah bahwa kepanjangan Ormas adalah “Organisasi Massa”, walaupun jelas tertulis dalam undang-undang sebagai “Organisasi Kemasyarakatan”. Makin salah jauh, terjemahan Ormas dalam dokumen bahasa Inggris pun banyak yang menuliskannya sebagai “Mass Organization”.
Ambiguitas ini, sedikit banyak telah menyelamatkan beragam jenis organisasi yang ada di sektor masyarakat sipil untuk tidak dicap sebagai Ormas. Dengan ketidakjelasan definisi Ormas dalam praktik, banyak organisasi bisa terhindar dari pendekatan politik-keamanan ala rezim Orde Baru. Sebagian besar kemudian secara hukum memilih bentuk Yayasan atau Perkumpulan, lalu secara sosial-politik berhasil membedakan diri dari Ormas.
Perebutan Tafsir Berulang Lagi
Tak banyak yang sadar bahwa perebutan tafsir kini sedang berlangsung lagi. Percobaan memadankan istilah Ormas dengan OMS mulai muncul di berbagai peraturan perundang-undangan. Definisi Ormas versi luas dibangkitkan lagi lewat UU Ormas tahun 2013, yang kemudian diubah dengan Perppu Ormas tahun 2017.
Lebih bermasalah dari versi Orba, UU Ormas terkini malah tegas mencampuradukkan badan hukum Yayasan dan Perkumpulan dalam pengertian Ormas. Dimasukannya Yayasan dan Perkumpulan dalam pegertian Ormas, benar-benar menimbulkan kerancuan baik secara hukum maupun praktiknya.
Sampai Juli 2020 tercatat ada 250.807 Yayasan, dan 174.402 Perkumpulan terdaftar. Kita tahu bersama, di antara 400-ribuan Yayasan dan Perkumpulan itu, ada Rumah Sakit, Universitas, Sekolah, Lembaga Filantropi, Panti Asuhan, Ornop/LSM, Pesantren, Rumah Ibadah, Sanggar Seni, Perkumpulan hobby dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita mau pukul rata, dan jadikan semuanya Ormas?
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai saat ini belum memukul rata seperti kekhawatiran di atas. Walaupun sama-sama berbentuk Yayasan, tapi Rumah Sakit, Kampus, atau Sekolah sampai sekarang belum dimasukkan oleh Kemendagri ke dalam kategori Ormas. Namun di sisi lain, ketika menjelaskan soal total jumlah Ormas kepada publik, Kemendagri selalu menyebut keseluruhan angka 400-ribuan organisasi itu sebagai Ormas. Nampaknya, ada kerancuan dan kebingungan atas tafsir Ormas, bahkan di kalangan pemerintah sendiri.
Tafsir bahwa Ormas sama dan sebangun dengan OMS, hadir juga dalam berbagai peraturan lain. Misalnya, PP No.45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, atau Perpres No.16/2018 (telah diubah Perpres No.12/2021) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kesemuanya seolah menempatkan Ormas sebagai kata ganti dari OMS.
Berbeda dengan aktivis LSM era 80-an yang melawan dengan tafsir tandingan, OMS masa kini belum memberikan perlawanan tafsir atas definisi Ormas yang luas. Walaupun UU Ormas lahir dengan penuh kontroversi dan penolakan masyarakat yang masif, namun UU ini dalam pelaksanaannya belum mendapatkan tentangan yang berarti.
Kemendagri kemudian menyelenggarakan berbagai kegiatan melibatkan OMS, termasuk dengan memberikan penghargaan “Ormas Awards”. Beberapa OMS menyambut baik kegiatan penghargaan ini, dan ikut merayakan statusnya sebagai Ormas terbaik di bermacam kategori.
Sebagian OMS agaknya bingung dengan kerangka hukum yang memang rancu. Sebagian lagi memilih menundukkan diri pada UU Ormas, semata karena pertimbangan pragmatis. Kenyataannya, mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk jadi Ormas memang jauh lebih mudah ketimbang pengurusan status Badan Hukum Yayasan atau Perkumpulan. Dalam pertimbangan pragmatis, yang penting organisasi bisa beroperasi dengan dukungan status legal, apapun bentuk statusnya.
Perlu Mendorong Tafsir Baru
Belajar dari sejarah LSM era 80-an yang berhasil mendorong tafsir tandingan, OMS saat ini juga perlu mendorong adanya tafsir baru tentang definisi Ormas. OMS perlu mulai membangun ruang tafsirnya sendiri yang membuat OMS jadi bisa mendefinisikan dirinya sendiri, apakah organisasinya merupakan sebuah Ormas atau bukan.
Pemerintah juga belum seragam dalam penggunaan istilah. Kadang Ormas, LSM, Organisasi Non-Pemerintah, kadang juga Lembaga Nirlaba. Berbeda dengan Orba, pemerintah hari ini nampak tidak satu suara dalam upaya “meng-ormas-kan” seluruh sektor masyarakat sipil. Lihat saja RPJMN 2020-2024 (Perpres No.18/2020) yang menggunakan istilah OMS, bukan Ormas, dalam arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi. Kementerian Hukum dan HAM juga sepertinya menyadari kerancuan yang ditimbulkan UU Ormas. Dalam Naskah Akademik RUU Perkumpulan (2016), Badan Pembinaan Hukum Nasional sepakat dengan argumen Penulis bahwa UU Ormas menambah ketidakpastian hukum (karena menempatkan Ormas seolah sebagai payung dari seluruh organisasi sosial), dan merekomendasikan agar pengaturan Perkumpulan seharusnya terpisah dari UU Ormas.
Masih ada peluang bagi OMS untuk mendesakkan tafsir alternatif untuk mengurangi kerancuan definisi Ormas. Ada perbedaan konsep dan praktik tentang definisi Ormas yang multi-tafsir. OMS perlu mendorong tafsir baru di tataran praktik, bahwa tidak semua OMS otomatis wajib jadi Ormas. Secara persisten OMS harus terus mendesakkan penggunaan istilah OMS, dan segera menyatakan keberatan tiap hendak dipukul rata sebagai Ormas.
Pastinya perlu ada perubahan undang-undang untuk meluruskan kerancuan ini. Pengaturan OMS sebaiknya dikembalikan kepada kerangka hukum yang benar yaitu: 1) UU Yayasan untuk OMS yang tidak berbasis anggota, 2) UU Perkumpulan untuk OMS yang berbasis anggota. Adapun terkait bidang kegiatan masing-masing (misal: kesehatan, pendidikan, penelitian, keagamaan dll), OMS bisa berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang sesuai bidangnya. Dengan begini, tidak ada Kementerian/Lembaga yang bertindak seakan jadi “Big Brother Institution” ala Orwell yang memayungi semua jenis OMS lintas bidang kegiatan.
Perebutan tafsir ini bukan sekadar urusan teknokratik revisi bunyi pasal belaka. Perlu disadari bahwa fenomena “shrinking civic space” sedang terjadi juga pada sektor masyarakat sipil di Indonesia. Dalam ruang yang menyempit, publik perlu bersiap dan menentang bermunculannya upaya menyempitkan ruang gerak organisasi, mempersulit perizinan, mendiskreditkan, menutup akses pendanaan, mengkriminalisasi, ataupun tindakan sewenang-wenang lainnya terhadap OMS. Sektor masyarakat sipil ini perlu dijaga bersama, untuk memastikan tersedianya ruang bebas dalam membuat perubahan.
*)Eryanto Nugroho, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Dosen STH Indonesia Jentera.