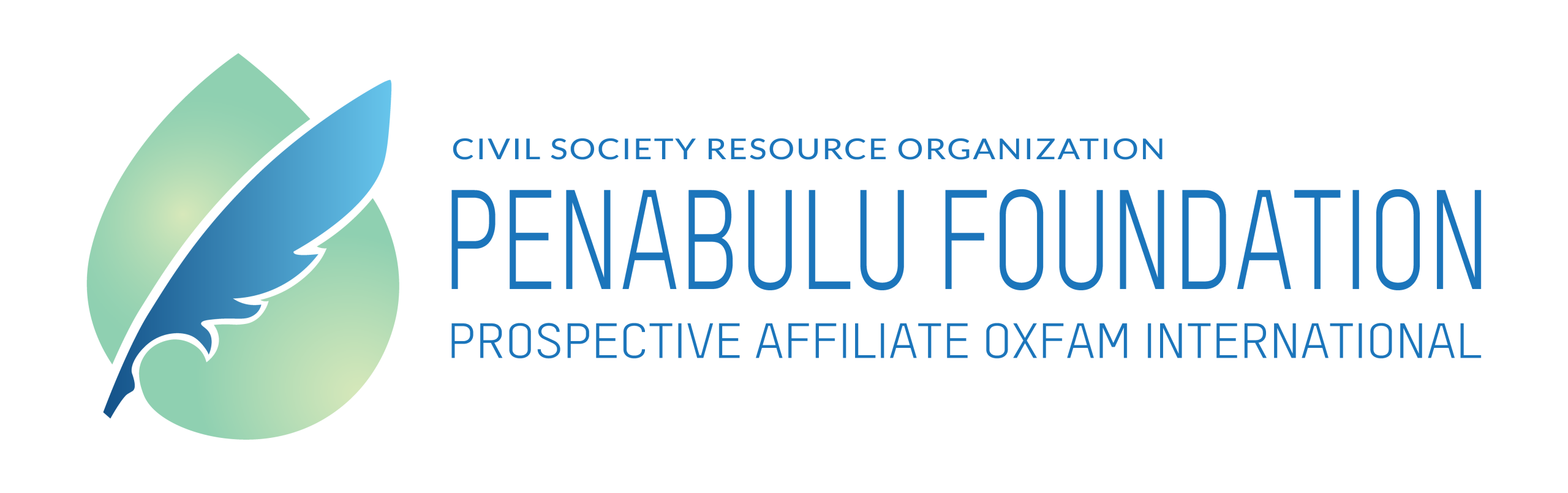Pertama, melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan belasungkawa terhadap wafatnya 6 warga negara, dalam hal ini anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) akibat bentrokan dengan aparat di jalan Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di kilometer 50, pada Senin (7/12/2020) dini hari.
Bagi saya, diluar konteks pro dan kontra dalam hal politik, hilangnya nyawa seseorang –apalagi beberapa orang- tidak dapat ditolerir. UUD 1945 sudah menjamin pada Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bahkan pada Pasal 28I disebutkan bahwa hak hidup menjadi salah satu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Non-derogable rights). Terlebih nyawa yang hilang itu bukanlah dari seseorang atau kelompok kriminal, teroris, atau ancaman kedaulatan yang butuh penanganan ekstra seperti kasus penembakan tersebut. Sehingga, pada titik, penegakan hukum yang berkeadilan harus dilakukan.
Dalam tulisan ini, saya tidak bicara versi kejadian penembakan siapa yang paling benar, karena kedua belah pihak (Polri dan FPI) punya versi yang berbeda. Tapi pada prinsipnya, bagi saya, setiap orang tanpa kecuali harus patuh kepada hukum, karena konstitusi jelas menyebut negara kita sebagai negara hukum. Namun pada saat yang sama, aparat juga tidak boleh sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Soal kasus penembakan secara umum, saya berhenti disini, sembari menekankan perlunya dibentuk Tim Pencari Fakta yang independen untuk mencari kebenaran kasus ini.
Dalam tulisan ini, yang ingin saya soroti adalah masuknya senjata kedalam dinamika demokrasi. Kalau pun dalam dinamika demokrasi itu dilaksanakan penegakan hukum, tentu bentuk paling jauh adalah melumpuhkan ketika seorang pelaku tindak pidana kejahatan melawan aparat atau membahayakan masyarakat sekitar. Aparat seharusnya sudah khatam dalam hal melumpuhkan ini, termasuk titik mana saja yang harus ditembak untuk melumpuhkan tersebut, karena telah dibekali pelatihan. Hukuman mati pun tentu harus melalui meja hijau terlebih dahulu. Sementara menembak mati, tentu domainnya sudah kill or to be kill yang lazim digunakan militer untuk melindungi negara dari ancaman terhadap pertahanan atau kedaulatan.
Implikasi masuknya senjata kedalam demokrasi adalah memupus nilai-nilai dalam demokrasi itu sendiri, seperti Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan hukum. Masuknya senjata tersebut tentu membuat orang tidak bebas berpendapat lantaran merasa terancam, hingga paling jauh dapat merenggut nyawanya. Ketika nyawa seseorang hilang akibat senjata tersebut, secara serta merta seluruh hak-hak yang melekat kepadanya juga direnggut. Begitu pun juga direnggut dari kehidupannya di keluarga dan masyarakat. Betapa mengerikannya senjata ini bila dibiarkan bergerak liar di alam demokrasi. Begitu pun apabila senjata itu dimiliki sipil secara illegal, juga tidak dapat dibiarkan.
Dengan persoalan demikian, maka sudah seharusnya pintu-pintu yang memungkinkan senjata itu masuk secara liar di alam demokrasi harus dikunci rapat. Penegakan hukum juga perlu diarahkan terhadap mereka yang menggunakan senjata tersebut tidak pada tempatnya. Tentu setelah yang bersangkutan terbukti bersalah. Namun proses yang dilakukan sampai kepada terbukti itu pun harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, karena ini juga menyangkut kepercayaan publik. Hilangnya nyawa ini bukan persoalan main-main.
Pada poinnya, jangan sampai pendekatan yang seharusnya dilakukan dalam ranah pertahanan negara, justru digunakan atau diadaptasikan seutuhnya pada ranah penegakan hukum dan ketertiban. Kita tentu juga harus rasional dalam melihat ancaman terhadap pertahanan atau kedaulatan negara, tidak boleh berlebihan. Namun jika bentuk ancamannya itu –terdeteksi- seperti invasi militer negara lain atau aksi terorisme yang diluar kemampuan penanganan Polri, tentu pendekatan militer memang perlu diutamakan, karena peruntukannya memang demikian.
Namun jika yang menjadi persoalan adalah suatu kelompok yang tidak bersenjata, hidup ditengah masyarakat seperti biasa, tidak menjadi bagian dari kelompok teroris, bahkan secara terang-terangan keberadaannya dapat diiendus, bagaimana mungkin pendekatan seperti halnya pendekatan akan perang digunakan? Sampai-sampai pasukan khusus gabungan militer turun tangan untuk menurunkan baliho dan menurunkan kendaraan taktis militer.
Ini jelas langkah yang berlebihan, bahkan potensial menjadi cerminan unjuk kekuatan penguasa terhadap pengeritiknya. Kalau pun pemerintah tidak mengintruksikan hal tersebut, melainkan inisiatif pribadi dari pihak militer, hal ini semakin perlu disoroti, karena mengarah kepada intervensi militer terhadap sipil. Lebih jauh, dalam kerangka relasi sipil-militer, jika pemerintah tidak mengevaluasi hal ini, juga potensial menjadi penggunaan atau pemanfaatan alat negara untuk kepentingan rezim, karena sama saja dengan mengaminkan tindakan tersebut. Meminjam istilah Samuel Huntington, fenomena tersebut merupakan relasi kontrol sipil subjektif (subjective civilian control). Kita tentu punya preseden buruk di Orde Baru soal pola relasi ini.
Pada titik ini, yang ingin saya sampaikan adalah dinamika demokrasi cukuplah diselesaikan dengan penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Evaluasi dan penegakan hukum perlu dilakukan untuk mereka yang punya senjata secara illegal, maupun aparat yang menggunakannya secara berlebihan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa beberapa orang. Meskipun kita perlu waspada terhadap setiap ancaman terhadap negara, tetapi jangan pula semua instabilitas politik di alam demokrasi diarahkan kepada potensi ancaman negara, seakan-akan instabilitas politik dalam demokrasi hanya bisa diselesaikan melalui senjata atau militer. Ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi.
Sumber: https://setara-institute.org/fpi-senjata-dan-demokrasi/